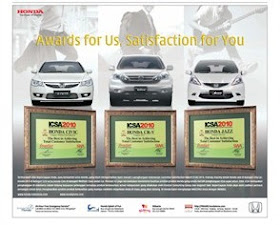PERTAMBANGAN
Menguak Hebatnya Aspal Buton
Oleh YUNI IKAWATI
Aspal alam hanya ditemukan di dua tempat di dunia ini, yaitu Trinidad dan di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Keberadaan sumber tambang ini telah diketahui pada 1920, tetapi tak tergali dengan baik. Inovasi lalu dilakukan untuk mengolahnya secara efisien hingga mampu menyaingi aspal dari minyak bumi yang mulai langka dan mahal.
Aspal merupakan salah satu material penting dalam pembuatan jalan di Indonesia. Namun, karena kelemahannya, yaitu mudah hancur akibat beban berat dan panas matahari serta genangan banjir, mendorong pihak pengelola menggunakan beton berangka besi. Padahal, beton relatif lebih mahal serta sulit pengerjaan dan perbaikannya.
Di antara dua material itu ada aspal alam yang lebih optimal dibandingkan keduanya. Aspal alam yang dikenal di dunia saat ini adalah Trinidad Lake Asphalt (TLA). Padahal, selain dari Pulau Trinidad di Laut Karibia itu ada aspal alam di Pulau Buton (Asbuton) yang sesungguhnya lebih unggul.
Dari segi cadangan, Asbuton jauh lebih besar dari TLA. Cadangannya mencapai 163,9 juta ton. Bahkan, perkiraan lain menyebutkan 450 juta ton, berarti tergolong terbesar di dunia. Usia pemanfaatan cadangannya ditaksir 200 tahun ke depan.
Meski kandungan aspal masih melimpah, sejak 1970-an, tambang ini mulai ditinggalkan karena tingginya biaya operasi yang tidak lagi sebanding dengan pendapatannya.
”Masalah sesungguhnya karena penerapan teknik ekstraksi atau pemurnian konvensional yang tak efisien,” kata Lisminto, penemu teknik baru pemurnian aspal Buton.
Dipisahkan
Pada proses lama, bitumen aspal lebih dulu dilarutkan dalam pelarut organik, lalu dipisahkan dari unsur pelarutnya dengan cara destilasi.
Dengan cara ini sulit menarik bitumen atau material aspal yang tersembunyi dalam matrik batuan induk. Karena itu, diperlukan ekstraktor bertahap banyak. Ini artinya perlu investasi besar.
Lisminto, lulusan S-1 Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) ini, berhasil menemukan teknik baru. Pada teknik baru itu, pelarutan aspal menggunakan kimia khusus dan proses pemurnian dilakukan dalam media air laut.
Saat batuan induk pecah, bitumen akan keluar dengan sendirinya dan mengapung di air asin. Karena itu, bitumen dengan mudah dapat dipisahkan dari larutan. Proses ini dilakukan pada suhu dan tekanan atmosfer sehingga memperkecil terjadinya pembakaran material. Sederhana, mudah, dan murah, itulah kelebihan teknik yang disebutnya ”pemurnian aspal Buton dengan teknologi ekstraksi terbalik”.
Inovasi ini sesungguhnya bukan lagi tergolong baru karena telah dipatenkan di lembaga paten Indonesia, Jepang, dan Australia pada 1996.
Aplikasi teknik ini, menurut dia, bisa menghemat devisa 75 juta dollar AS karena investasi total hanya 25 juta dollar AS dengan fabrikasi di dalam negeri. Sementara teknologi lain bisa mencapai 100 juta dollar AS.
Penggunaan sumber tambang di dalam negeri juga dapat menekan impor aspal sebesar satu juta ton per tahun sehingga tercipta swasembada aspal nasional. Sebab, teknologi ekstraksi terbalik ini dapat menghasilkan aspal berkualitas tinggi dengan harga terjangkau.
Hal ini memungkinkan jaringan jalan kelas satu sebagai infrastruktur industri juga berkembang. Dan, terbukanya industri di Buton akan membuka lapangan kerja penduduk sekitar.
Hasil samping
Meski inovasi itu memiliki prospek bisnis dan sosial yang baik, rupanya kemudian kurang mendapat sambutan pemerintah dan perusahaan pertambangan. Hal ini tak membuatnya patah semangat. Secara konsisten, Lisminto terus berkutat dengan riset aspal hingga pengembangan pabrik.
Pabrik percontohan berkapasitas satu ton per jam berhasil dibangun dengan dana Rp 200 juta. Produknya telah diuji Puslitbang Jalan Binamarga dan dinyatakan sebagai aspal bermutu. Uji laboratorium dan uji lapangan menunjukkan, sifat produknya setara dengan Trinidad Lake Asphalt.
Teknologi proses ini bahkan menghasilkan produk samping yang sangat potensial, yaitu gipsum dan karbon dioksida. Gipsum adalah bahan baku semen yang masih diimpor 2 juta ton per tahun. Adapun oksida karbon dapat dikonversi menjadi es kering guna mengawetkan ikan. Dari setiap ton produk aspal itu dihasilkan 1,45 ton gipsum dan 0,47 ton es kering.
Pengembangan baru
Melalui pengembangan aspal yang terus-menerus sejak 15 tahun lalu di laboratorium dan pabrik yang dijuluki ”Rumah Teknologi Aspal”, berhasil diatasi lima masalah yang ditemukan pada aspal Buton yang dibuat selama ini, yaitu soal adesivitas, kesulitannya dalam pengolahan, pemadatan, fleksibilitas, dan hambatan distribusinya.
Hasil olahan aspal Buton terbaru ini diberi nama BNA (Buton Natural Asphalt), yang didesain sebagai ”cloning” TLA.
Produk ini kemudian mulai menarik perusahaan lain untuk bermitra, antara lain Adhi Jaya, Pertamina, dan PT Timah (Persero).
Pertamina juga tertarik untuk ikut terlibat dalam pengembangan aspal Buton.
Pengembangan BNA diharapkan dapat mengikuti ”kisah sukses TLA” yang sudah terbukti sebagai bahan konstruksi andal selama lebih dari 100 tahun.***
Sumber : Kompas, Selasa, 4 Januari 2011 | 04:34 WIB
Ada 3 Komentar Untuk Artikel Ini. Kirim Komentar Anda
- Andrean Palonggam
Jumat, 7 Januari 2011 | 19:46 WIB
Hebat!!! Segera realisir..
- Benny Djutrisno
Rabu, 5 Januari 2011 | 14:19 WIB
Bu Yuni Ikawati dan Yth pak Lisminto,kami sangat mendukung upaya bapak yang tanpa kenal lelah,demi menghasilkan"Aspal Nasional" yang berkualitas "International".sampai jumpa lagi diseminar tentang ASPAL. Selamat Berjuang.
- joe gultom
Selasa, 4 Januari 2011 | 11:52 WIB
maju terus para peneliti Indonesia ^.^v